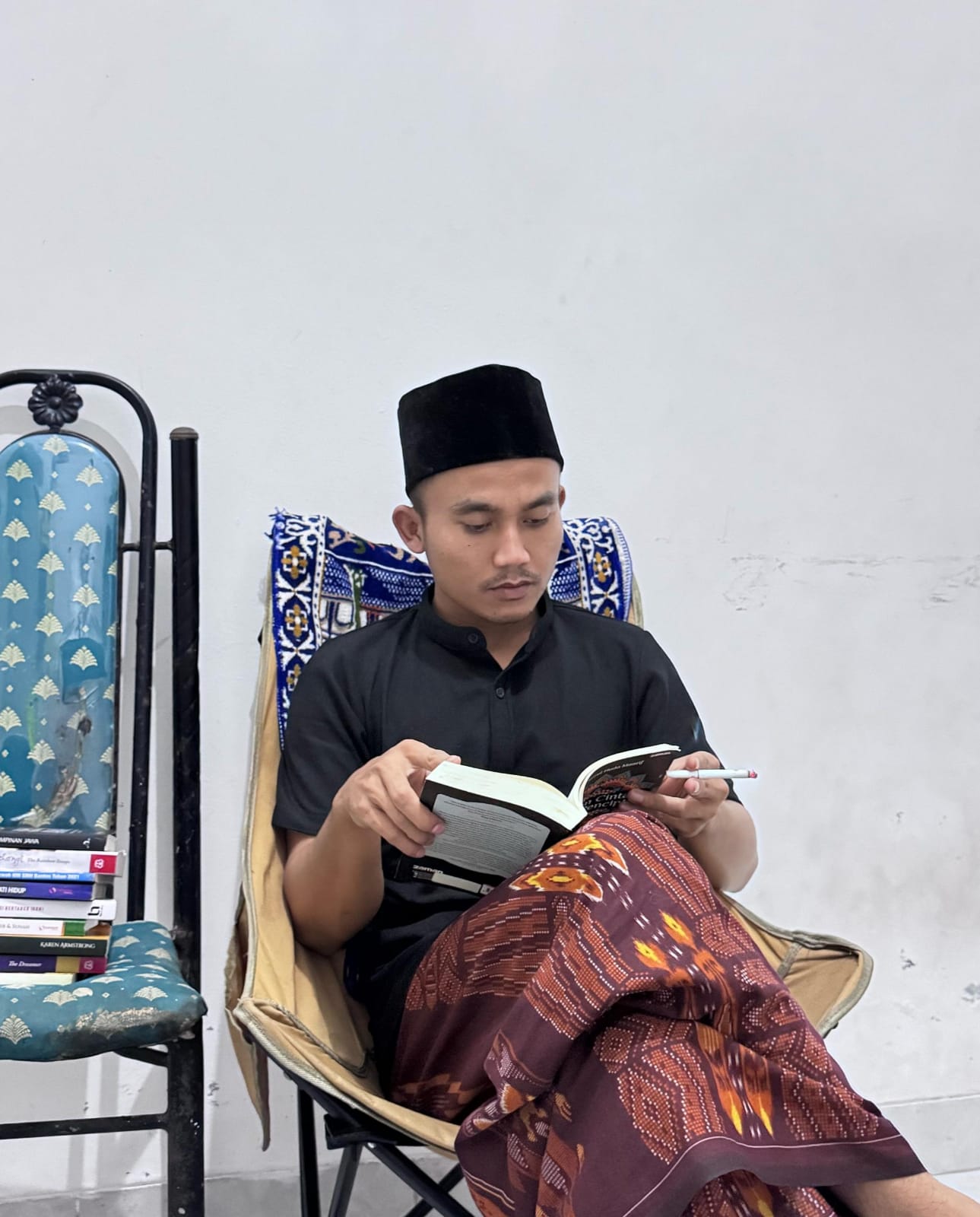Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 melalui UU No. 3 Tahun 2025 yang membuka kembali ruang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil merupakan kebijakan negara yang menuai kontroversi. Dalam perspektif pengkajian Islam, hal ini perlu dikaji lebih dalam, bukan hanya dari sisi legal-formal, melainkan juga dari sisi etika kekuasaan, prinsip keadilan (‘adl), dan kemaslahatan (‘maslahah)umat.
Islam menempatkan kekuasaan sebagai amanah, bukan alat dominasi. Dalam QS. An-Nisa [4]:58, Allah memerintahkan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
Kutipan ayat ini, menegaskan bahwa kekuasaan publik termasuk jabatan sipil, harus diberikan kepada pihak yang tepat, melalui mekanisme yang adil dan partisipatif, bukan semata karena latar belakang kekuatan atau kedekatan struktural dengan pusat kekuasaan.
Dalam sejarah Islam, khalifah Umar bin Khattab dikenal tegas dalam membatasi aparat yang memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan, sekalipun berasal dari kalangan yang dipercaya. Hal ini menunjukkan pentingnya checks and balances, serta kehati-hatian dalam menempatkan individu di posisi strategis. Maka, penunjukan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil, terutama tanpa proses partisipatif masyarakat, dapat dipandang sebagai bentuk istilah, ta’addî al-sulṭah, penyimpangan kekuasaan dari jalan keadilan.
Lebih jauh, prinsip maslahah atau kemaslahatan umat menjadi parameter utama dalam fikih siyasah. Menurut Imam al-Ghazali, maslahah tidak boleh hanya diukur dari efisiensi atau stabilitas administratif semata, tetapi harus mempertimbangkan perlindungan terhadap lima prinsip dasar (maqashid al-syari‘ah), agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Jika keterlibatan militer dalam ranah sipil justru menciptakan ketakutan, membatasi partisipasi warga, atau melemahkan demokrasi lokal, maka hal itu bertentangan dengan maqashid tersebut, meskipun mungkin tampak stabil secara lahiriah.
Dalam konteks ini, para ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, menekankan bahwa keadilan dan partisipasi merupakan fondasi dari negara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Negara yang mengabaikan suara rakyat dan mempersempit ruang publik adalah negara yang kehilangan ruh syura (musyawarah), sebagaimana diperintahkan dalam QS. Asy-Syura [42]:38:
“…dan (orang-orang) yang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”
Penempatan prajurit aktif ke dalam jabatan sipil tanpa keterlibatan masyarakat, jika dibiarkan berulang, berisiko membentuk model pemerintahan yang jauh dari semangat syura, dan dekat pada model kekuasaan elitis yang menutup ruang kritik.
Kesimpulan:
Dalam perspektif Pengkajian Islam, kebijakan apapun yang berdampak langsung pada tata kelola kekuasaan publik harus diuji melalui prinsip keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi. Keterlibatan militer dalam birokrasi sipil yang dilakukan tanpa keterbukaan dan akuntabilitas dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, umat Islam sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal arah kekuasaan agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan maslahat secara syar’i.